Edhi Sunarso, Sebuah Profil Maestro Seni Patung Indonesia
Melempar geranat kepada serdadu NICA (Nederlandsch Indie Civil Administratie) adalah pekerjaan Edhi Sunarso di usia 14 tahun. Sebelum menjadi seniman, Edhi yang lahir di Salatiga, 2 Juli 1932 memang seorang pejuang kemerdekaan. Ia adalah mantan Pasukan Samber Nyawa Divisi I, Bataliyon III, Resimen V Siliwangi.
 |
| Edhi Sunarso |
Karena karya-karyanya yang luar biasa maka negara telah menganggapnya berjasa besar terhadap bangsa dan negara dalam memajukan dan membina kebudayaan nasional. Sehingga, ia dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma pada 12 Agustus 2003.
Di samping itu, ia juga telah memiliki beberapa tanda penghargaan, yaitu: Lomba Seni Patung Internasional di Inggris The Unknown Political Prosoner (1953), Medali Emas dari Pemerintah India untuk Karya Seni Patung Terbaik (1956), Piagam Seni dari Pemerintah Republik Indonesia (1984), serta Piagam Seni dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Karya Monumental (1996).
Mengenai pameran, Ehi Sunarso telah beberapa kali mengadakan pameran, baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain: Pameran Tunggal di Santiniketan India (1956), Pameran Tunggal dan Pameran Nasional ALL India di India (1957), pameran bersama istri di Yogyakarta (1959), dan pameran bersama But Mohtar, G.Sidharta, dan Rita Widagdo (1987).
Di dunia pendidikan, ia sudah aktif sebagai staf pengajar pada Akademi Kesenian Surakarta sejak tahun 1958-1959. Tahun 1959-1967, ia mengajar di Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia (STSRI) ASRI Yogyakarta sebagai Ketua Jurusan Seni Patung. Pada 1967-1981, sebagai tenaga pengajar pada Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Negeri (IKIP) Yogyakarta. Tahun 1968-1984, sebagai pengajar merangkap asisten Ketua Bidang Akademik STSRI/ISI (Institut Seni Indonesia) Yogyakarta. Dan tahun 1985-1990, sebagai pengajar sekaligus Sekretaris Senat di ISI Yogyakarta.
Mengenai perjalanan hidupnya sampai menjadi pematung, juga menarik untuk dipaparkan. Sebenarnya, dulu Edhi ingin jadi mekanik. Namun, keadaan menggiringnya jadi seniman.
Sejak usia 7 bulan, anak dari Somo Sardjono ini sudah harus berpisah dengan kedua orang tuanya. Hari kelahirannya, Selasa Wage, ternyata sama dengan Ayahandanya. Dalam tradisi Jawa, ada istilah tumbuk weton, yaitu jika hari kelahiran anak pria sama dengan ayahnya maka dipercaya hal ini dapat membawa kesialan, sehingga keduanya harus dipisah. Akhirnya, Edhi Sunarso dibawa ke daerah Kemayoran, Jakarta dan diasuh oleh Budenya.
Saat Jepang masuk ke Jakarta dan membombardir beberapa lokasi di ibukota, termasuk rumah Budenya Edhi, ia terpisahkan dari Budenya yang lari mengungsi entah kemana. Edhi pun langsung dibawa oleh seorang guru ke Pegaden Baru di Subang dan diangkat menjadi anak.
Kemudian, perang kemerdekaan berkobar. Edhi yang masih berusia belasan tahun, bergabung dengan pejuang gerilyawan Indonesia untuk melawan Belanda. Saat itu ia bertugas menjadi kurir, yaitu penghubung antar pejuang kemerdekaan. Ketika kelas 5 Sekolah Rakyat (SR), ia tinggalkan sekolahnya dan mulai bergerak sebagai pasukan sabotase yang membakar pabrik-pabrik milik Belanda.
Ketika di Cimalaya, Edhi Sunarso beserta pasukannya yang berjumlah 19 orang dikepung oleh Belanda. Sejak itulah hampir selama empat tahun, ia hidup dari penjara ke penjara dan merasakan siksaan. Dan di penjara inilah Edhi berkenalan dengan seni. Tiap hari ia ditugasi menggambar dan bikin kerajinan.
Pada usia 16 tahun, Edhi Sunarso diperbolehkan untuk keluar dari penjara. Saat mendengar keputusan itu, bukannya senang, ia justru khawatir karena tidak tahu akan pergi ke mana.
Lalu, Edhi berniat bergabung lagi di Divisi Siliwangi. Tapi, ketika itu induk pasukannya sedang tugas ke Yogyakarta. Ia pun berjalan kaki dari Bandung ke Semarang dan dapat nunutan ke Jogya. Sampai di Jogja, eh, ternyata induk pasukan Divisi Siliwangi sudah balik ke Bandung.
Nasib Edhi pun terkatung-katung. Untuk menyambung hidup, ia jadi tukang semir di Stasiun Tugu. Kemudian, ia lapor ke markas TNI di Yogya dan diberi opsi: melanjutkan karier Militer atau sekolah. Setelah berfikir–sadar usianya masih muda dan hanya sempat sekolah sampai kelas 5 SR–Edhi memilih keluar dari dinas militer. Tapi, ia juga bingung cari sekolah karena tidak punya ijazah.
Di tengah kebingungannya (saat itu tahun 1950), ada akademi baru ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) yang mengingatkan Edhi kepada kebiasaan dan bakat yang dipupuk saat meringkuk di tahanan. Edhi pun setiap hari ke kampus ASRI untuk melihat mahasiswa yang sedang praktik.
Karena tiap hari nongkrong di kampus ASRI dengan pakaian itu-itu saja–seragam militer dengan cap tahanan Belanda–maka menarik perhatian Hendra Gunawan, seorang perupa dan dosen. Hendra pun mendekati dan bertanya, “Apakah Edhi ingin sekolah di ASRI?” Spontan jawabnya : “Saya Ingin!”
Walaupun tak punya ijazah, atas lobi Hendra kepada Direktur ASRI, Amoroso Katamsi, maka Edhi diterima menjadi mahasiswa “dengar”. Edhi tidak ikut kuliah teori di kelas dan hanya mendengarkan dan mengikuti praktik di lapangan.
Saat Monumen Simpang Lima Semarang dibangun (oleh Hendra Gunawan), Edhi dipercaya jadi koordinator pelaksana. Monumen itu diresmikan Bung Karno, yang sempat terkesima dan mencari Edhi Sunarso. Di sinilah Edhi berkenalan dengan Bung Karno.
Pada 1955 hingga 1957, Edhi memperoleh beasiswa dari Unesco untuk belajar di Visva Bharaty University di Santiniketan, India. Akhir 1997 ia pulang ke tanah air dan menjabat sebagai ketua Jurusan Seni Patung di ASRI.
Selanjutnya, Edhi dipanggil Bung Karno dan ditantang membuat patung perunggu setinggi 9 meter (Tugu Selamat Datang yang berdiri di Bundaran HI). Edhi mengaku tidak sanggup. Patung sebesar itu dengan bahan perunggu bukan karya yang mudah. Bung Karno pun memaksa dan mengatakan, kalau Edhi punya rasa cinta tanah air, pasti bisa.
Edhi langsung pulang ke Jogja menghubungi beberapa seniman, termasuk menghubungi para pensiunan PJKA dan eks anggota Brigade Tentara Pelajar Solo, untuk mengerjakan pengecoran. Mereka pun setuju dan siap membantu meskipun dengan alat sederhana. Dalam waktu setahun, kerjaan pun selesai.
Dengan pertimbangan keseimbangan, tinggi patung menjadi 8,5 meter. Meskipun begitu, Bung Karno dan Ir Sutami, Menteri PU saat itu, tak mempermasalahkannya. Bung Karno puas. Sejak itulah Edhi Sunarso dipercaya sebagai pematung dan mendapat proyek-proyek patung monumen yang lain, seperti Patung Dirgantara yang berdiri di Prapatan, Jakarta dan Monumen Nasional (Monas).
Tentang Patung Dirgantara, ada cerita menarik. Ongkos pembuatannya sekitar Rp 12 juta. Edhi baru dibayar Rp 7,5 juta. Saat itu posisi Bung Karno kritis, tak bisa mencairkan dana pemerintah. Edhi pun menjual mobil dan barang berharga lainnya buat belanja bahan dan membayar pekerja. Bahkan setelah patung jadi, Bung Karno minta agar patung segera dipasang. Maka Edhi berkata, “Dari mana dananya? Saya sudah tak punya uang...”
Lalu, Bung Karno menyuruh ajudannya menjual salah satu mobil pribadi Bung Karno untuk biaya pasang patung. Mobil laku Rp 1,2 juta. Waktu pemasangan, setiap minggu Bung Karno datang ke lokasi. Masyarakat pun memberi sambutan yang luar biasa. Tapi, ini membuat Pak Harto cs, gerah. Akhirnya, Bung Karno dilarang keluar rumah sejak itu.
Sepeninggal Bung Karno, Edhi Sunarso tetap dipercaya menggarap patung dan monumen perjuangan. Beberapa karyanya, antara lain: Monumen Pembebasan Irian Barat di Jakarta, Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya dan dioramanya di Jakarta, Monumen Jenderal Ahmad Yani di Bandung, Monumen Jenderal Gatot Subroto di Surakarta, Monumen Pahlawan Samudera Yos Sudarso di Surabaya, Monumen Yos Sudarso di Biak, Monumen Sultan Thaha Syafudin di Jambi, dan diorama Sejarah Museum Yogya Kembali di Yogyakarta.
Mengenai keluarga, Edhi menikah dengan wanita bernama Kustiyah, yaitu seorang pelukis kelahiran Purbalingga yang merupakan adik kelas waktu di ASRI. Dalam pernikahannya, Edhi dikaruniai 4 orang anak, yaitu: Rosa Arus Sagara, Titiana, Irawani, Satya Sunarso, dan Sari Prasetyo Angkasa. (Yunisa Priyono, Almanak Seni Rupa Jogja 1999-2009)
Sumber:
Minggu Pagi, edisi No 23 Tahun 56, 1 September 2003
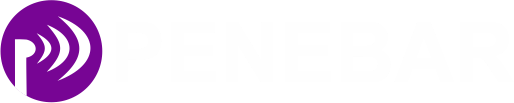
Diskusi